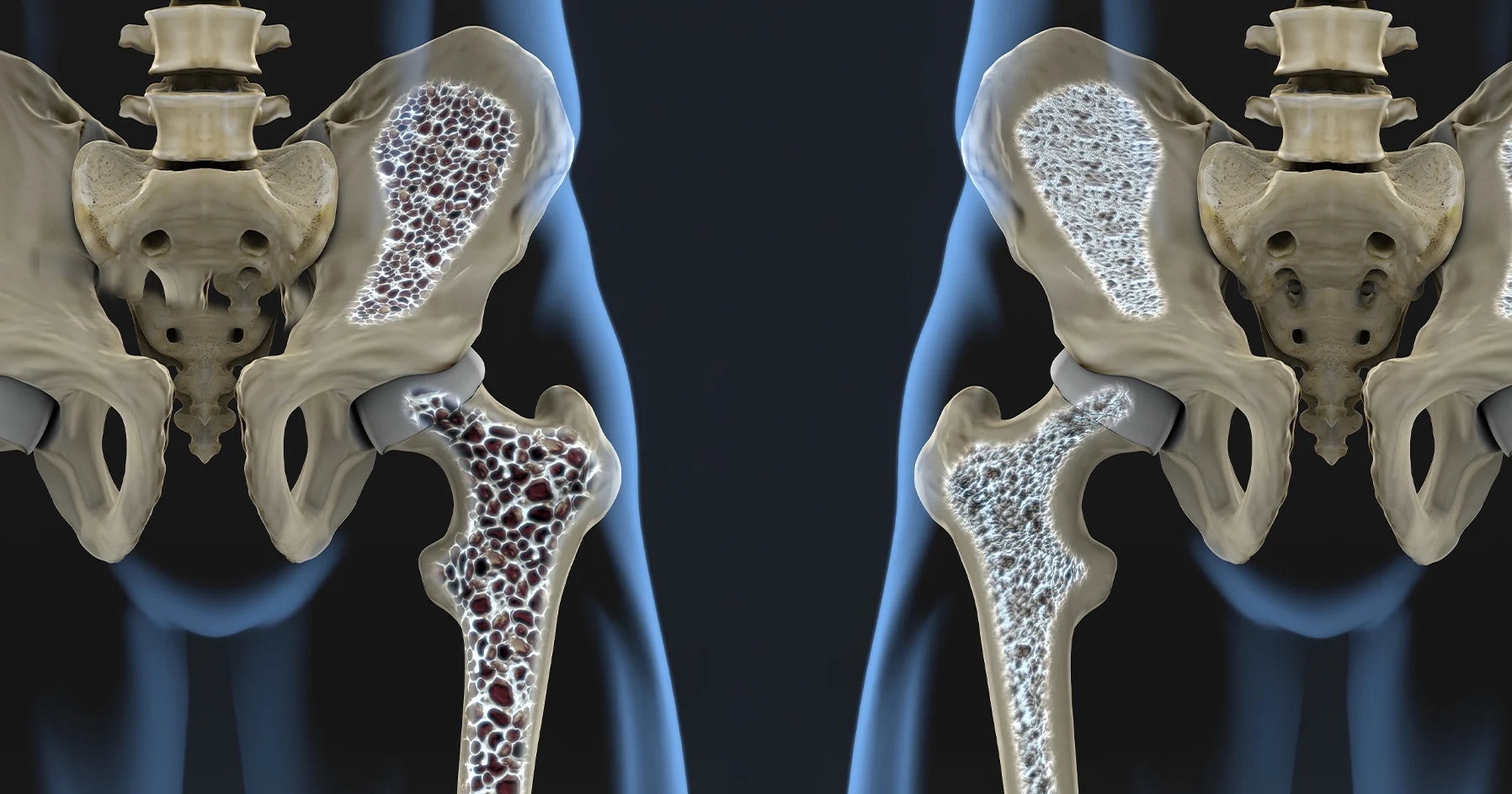Jakarta, incahospital.co.id – “Waktu SD, saya sering dibilang aneh. Padahal saya nggak bisa ngontrol. Kadang tiba-tiba mata saya kedip terus atau saya ngeluarin suara tanpa sadar,” ujar Adit, 25 tahun, yang baru tahu bahwa dirinya mengidap Tourette Syndrome saat kuliah.
Tourette Syndrome—atau dalam bahasa medis dikenal sebagai TS—adalah gangguan neurologis yang ditandai dengan tics, yaitu gerakan atau suara yang terjadi berulang tanpa bisa dikendalikan oleh penderitanya. Bukan karena mereka iseng, bukan juga karena kurang sopan. Ini murni kondisi medis yang berasal dari sistem saraf pusat.
Tics bisa berupa gerakan fisik (motor tics), seperti mengedipkan mata, menggelengkan kepala, atau mengangkat bahu. Ada juga vocal tics, seperti bersuara “uh”, batuk, atau dalam kasus ekstrem bisa mengeluarkan kata-kata kasar (coprolalia)—meskipun yang terakhir ini hanya terjadi pada sekitar 10–15% penderita TS.
Indonesia mungkin belum banyak bicara soal TS. Tapi di luar negeri, beberapa tokoh terkenal seperti Billie Eilish dan Lewis Capaldi secara terbuka menyampaikan bahwa mereka hidup dengan kondisi ini. Di sinilah pentingnya edukasi: supaya publik tak buru-buru menghakimi seseorang hanya karena perilaku yang terlihat “aneh”.
Penyebab Tourette—Antara Genetika dan Sistem Dopamin

Kalau ditanya, apa penyebab pasti Tourette Syndrome? Jawabannya belum 100% jelas. Namun sebagian besar riset sepakat bahwa faktor genetik dan neurokimia otak sangat berperan.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa TS berkaitan dengan kelainan pada sirkuit otak yang mengatur gerakan dan perilaku, terutama pada bagian basal ganglia, korteks frontal, dan sistem neurotransmitter seperti dopamin.
Anak yang punya riwayat keluarga dengan gangguan tics atau gangguan obsesif-kompulsif (OCD) berisiko lebih tinggi mengembangkan TS. Tapi tentu saja, tidak semua yang punya genetik tersebut akan menunjukkan gejala.
Biasanya TS mulai muncul antara usia 5 hingga 10 tahun. Pada banyak kasus, gejalanya akan mencapai puncak di masa remaja dan perlahan mereda saat dewasa. Namun pada sebagian kecil orang, gejalanya bisa menetap seumur hidup.
Satu hal yang menarik: meski tampak sebagai “gangguan”, banyak penderita TS yang memiliki kemampuan kognitif tinggi. Bahkan beberapa anak dengan TS menunjukkan kecerdasan di atas rata-rata, terutama dalam bidang musik, seni, atau matematika.
Hidup Bersama Tourette di Tengah Masyarakat yang Belum Siap
Di lingkungan tempat Adit tumbuh, tak banyak yang paham soal Tourette. Ia sering dikira kerasukan, kurang ajar, bahkan dicap pembuat onar karena kadang bersuara aneh saat kelas berlangsung.
“Saya sempat kena skors gara-gara dikira sengaja bikin ribut di ruang ujian. Padahal saya gak bisa nahan suara-suara itu,” kisahnya. Baru saat kuliah psikologi, ia sadar bahwa tics yang ia alami punya nama dan bisa dijelaskan secara medis.
Sayangnya, stigma seperti ini masih sangat kuat di Indonesia. Minimnya informasi membuat banyak guru, orang tua, bahkan tenaga medis mengabaikan atau salah mengartikan Tourette sebagai masalah kepribadian, bukan neurologis.
Padahal, dengan pemahaman yang tepat, anak-anak dengan TS bisa berkembang optimal. Mereka hanya perlu ruang, dukungan, dan pemahaman. Dalam beberapa kasus, terapi perilaku seperti CBIT (Comprehensive Behavioral Intervention for Tics) terbukti membantu mengurangi frekuensi dan intensitas tics.
Yang lebih penting dari segalanya: penderita TS butuh diperlakukan dengan hormat. Mereka bukan objek lelucon, mereka bukan “orang aneh”. Mereka hanya berbeda sedikit cara, tapi tetap manusia utuh yang bisa produktif.
Ketika Tourette Bertemu Dunia Digital—Antara Awareness dan Eksploitasi
Dunia digital, terutama media sosial, punya dua sisi dalam isu Tourette.
Di satu sisi, platform seperti YouTube dan TikTok membuka ruang bagi penderita TS untuk berbagi pengalaman. Beberapa konten kreator seperti Tourettes Teen, Neurodivergent Rebel, atau bahkan Billie Eilish sendiri, menjadikan media sosial sebagai tempat edukasi publik.
Namun di sisi lain, muncul pula konten viral yang menjadikan TS sebagai hiburan. Tics dijadikan bahan lucu-lucuan, bahkan ditiru sebagai “challenge”. Ini sangat merugikan, karena memperkuat stigma bahwa TS hanyalah gimmick atau sensasi.
Psikolog dari Jakarta, dr. Laras Permata, dalam sebuah wawancara menyebutkan bahwa semakin banyak anak remaja yang datang ke kliniknya dengan “tics fungsional”—gejala mirip TS tapi dipicu oleh konsumsi konten yang tidak tepat di TikTok.
“Bukan berarti mereka pura-pura. Tapi ini bentuk sugesti yang kuat dari media. Anak yang punya kecemasan bisa mengembangkan tics hanya karena terlalu banyak nonton konten tertentu,” ujar dr. Laras.
Karena itu, edukasi tetap penting, Tidak semua yang terlihat lucu bisa dicerna tanpa pemahaman. Tidak semua yang viral pantas ditiru.
Menuju Masyarakat Inklusif—Apa yang Bisa Kita Lakukan?
Kita tidak perlu jadi dokter saraf untuk membantu penderita Tourette. Kadang, cukup jadi manusia yang mau belajar dan peduli.
Langkah kecil yang bisa dimulai:
-
Tidak mengolok-olok tics, apapun bentuknya.
-
Jika mengenal teman, murid, atau saudara dengan gejala TS, arahkan mereka untuk konsultasi dengan psikolog atau dokter spesialis saraf.
-
Dorong sekolah dan lingkungan kerja untuk lebih terbuka terhadap kebutuhan khusus.
-
Edukasi lewat komunitas, organisasi kampus, atau media sosial pribadi.
Di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, mulai muncul komunitas neurodivergent yang membuka ruang aman bagi penderita Tourette, ADHD, dan gangguan spektrum lain. Mereka tidak hanya menjadi tempat curhat, tapi juga jembatan ke layanan profesional.
Pemerintah juga sudah mulai memberi perhatian, meski belum ideal. Dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, gangguan neurologis seperti TS masuk dalam daftar kelompok yang harus dilindungi haknya. Tapi implementasinya? Ya, masih banyak PR.
Semoga dengan makin banyaknya suara-suara personal dari penderita Tourette yang diangkat ke permukaan, kita semua jadi lebih peduli. Karena masyarakat yang inklusif bukan dilihat dari megahnya aturan, tapi dari kecilnya diskriminasi yang terjadi sehari-hari.
Penutup:
Tourette Syndrome bukan akhir. Ia hanyalah bentuk lain dari kompleksitas otak manusia.
Bagi yang hidup dengannya, setiap hari adalah perjuangan antara mengendalikan tubuh dan tetap terlihat “normal” di mata orang lain. Tapi mereka tidak minta dikasihani. Yang mereka butuhkan hanyalah pemahaman.
Dan untuk kita semua yang mungkin belum tahu, inilah saatnya belajar. Karena semakin kita tahu, semakin kecil ruang untuk salah paham.
Tourette adalah kisah tentang perjuangan, tentang keberanian jadi diri sendiri di dunia yang tak selalu ramah pada perbedaan. Dan mungkin, di antara tics dan kedipan tak sadar itu, tersimpan semangat hidup yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan.
Baca Juga Konten Dengan Artikel Terkait Tentang: Kesehatan
Baca Juga Artikel Dari: Air Minum Bersih: Rahasia Hidup Sehat Tanpa Drama Setiap Hari